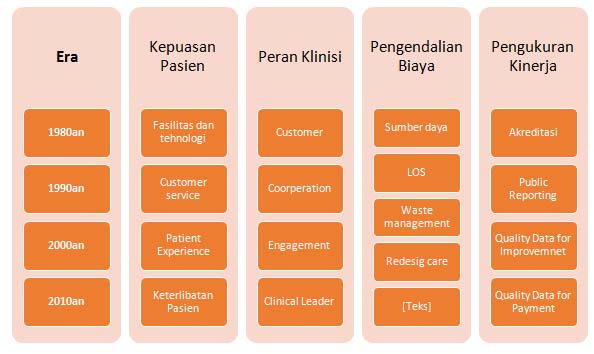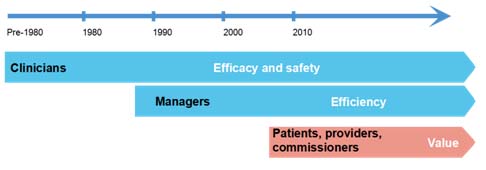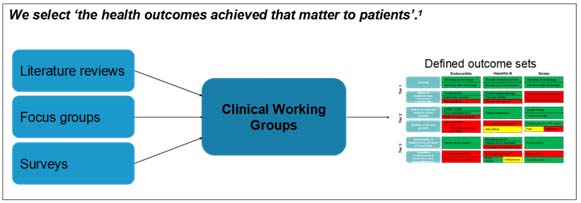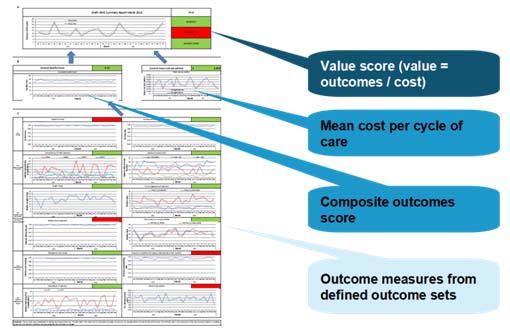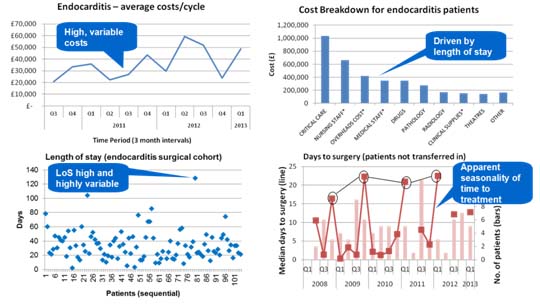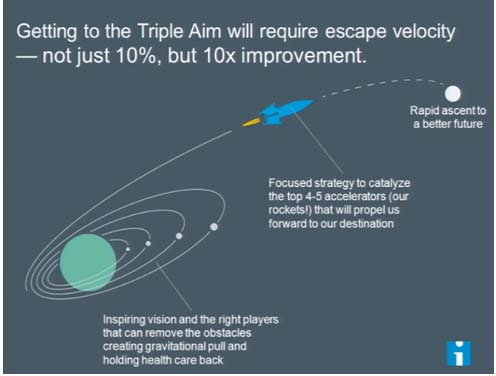Salah satu tantangan dalam pengelolaan rumah sakit menghadapi akreditasi sistem yang baru adalah masalah keselamatan. Gerakan keselamatan pasien menjadi urat nadi sistem akreditasi rumah sakit. Walau mengadopsi sistem dari Joint Comission International (JCI), nampak bahwa Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) ingin mengedepankan mutu dan keselamatan pasien sebagai panglima dalam akreditasi rumah sakit.
Selain keselamatan pasien, kewaspadaan terhadap kebakaran dan kebencanaan adalah bagian dari sistem akreditasi dan berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan, pengelolaan limbah, pengelolaan sistem utilitas (listrik, air, gas, pengatur suhu, dan lain-lain), dan pengelolaan alat medis. Berbagai titik tangkap mengenai keselamatan ini menunjukkan bahwa sarana gedung, lokasi bangunan, dan sistem pendukung kebencanaan yang ada di rumah sakit sering kali belum layak. Banyak rumah sakit di Indonesia dibangun tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan dalam rancangannya. Dalam persiapan akreditasi, rumah sakit kemudian menyiasati berbagai kekurangan ini.
Salah satu perencanaan yang komprehensif dalam hal kebencanaan sering disebut sebagai hospital disaster plan atau sering disingkat dengan HDP. Dokumen HDP sering hanya berhenti pada penyusunannya saja dan lupa diuji coba untuk melihat kelayakan penerapannya. Banyak yang lupa, bahwa perencanaan sering kali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Simulasi bencana, dengan demikian, sebenarnya adalah bagian tidak terpisahkan dari penyusunan HDP.
Rumah Sakit Panti Rapih, tempat penulis berkarya, juga memiliki HDP. Kami menyebutnya rencana penanggulangan bencana rumah sakit, atau kami singkat sebagai RPBRS. Dokumen RPBRS ini merupakan kerja bersama seluruh unit kerja di RS Panti Rapih dikoordinasi oleh panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) dan tim manajemen risiko. Dalam penyusunannya, tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) dan komite pengendalian infeksi rumah sakit (KPIRS) juga ikut berkiprah.
Dalam menyusun RPBRS, seluruh unit kerja diminta membuat perencanaan apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana. Setelah perencanaan unit terkumpul, dibantu suatu draft, dokumen disusun. Penyusunan dokumen diikuti dengan rapat dan diskusi. Rapat dan diskusi menghasilkan kesepakatan bersama. Salah satu contoh kesepakatan bersama yang dicapai lewat rapat dan diskusi adalah penetapan jalur evakuasi, pembukaan titik kumpul aman, dan zona pelayanan triase. Pendek kata, RPBRS kami merupakan pemberdayaan seluruh unit.
Dokumen RPBRS mengatur perencanan sistem komando saat bencana, evakuasi pasien rawat inap, kelanjutan perawatan pasien di titik kumpul aman, pengelolaan pengunjung dan keluarga pasien, prioritisasi penanganan korban dari luar rumah sakit, aktivasi sistem pendukung pelayanan, dan asesmen bangunan dan sistem utilitas. Rencana tersebut kemudian disosialisasikan ulang kepada seluruh unit kerja, dengan dua cara. Cara pertama dilakukan di unit kerja masing-masing. Tim RPBRS berkeliling ke seluruh unit kerja untuk bicara mengenai RPBRS dan tugas secara spesifik apa yang dibebankan pada unit kerja tersebut. Cara kedua adalah dengan cara klasikal. Cara klasikal diberikan kepada para kepala unit kerja saat pertemuan dan pada karyawan baru atau baru diangkat.
Setelah fase sosialisasi selesai, kami adakan simulasi. Simulasi besar yang diadakan 6 April 2014 yang lalu bekerja sama dengan Akademi Keperawatan Panti Rapih (memperagakan pasien internal dan eksternal) dan Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Denbekang) IV-44-02 di bawah Pangdam IV Diponegoro. Simulasi ini bertujuan menguji RPBRS dan menetapkan perencanaan untuk perbaikan di masa depan. Pada simulasi ini, kami memilih bencana gempa dan memakai situasi gempa tahun 2006.
Dalam simulasi ini, tim manajemen risiko menempatkan evaluator-evaluator di berbagai titik penting di RS Panti Rapih dan membuat asesmen mengenai jalannya simulasi. Ada beberapa catatan penting paska simulasi yang telah dibuat, misalnya mengenai kualitas triase, waktu yang dibelanjakan untuk identifikasi pasien, alur pasien saat evakuasi, pelayanan pasien di titik kumpul aman, dan lain-lain.
Salah satu contoh masalah dalam perencanaan adalah mengenai identifikasi pasien eksternal. Kami merencanakan untuk menuliskan dua identitas (nama dan tanggal lahir) pada gelang dan memberikan label triase. Kami mengingat bahwa identifikasi yang benar adalah sasaran pertama dari keenam sasaran keselamatan pasien. Logikanya, akan lebih aman bagi pasien bila identitas tersebut telah dibereskan sebelum pasien dilayani di zona pelayanan triase merah, kuning, dan hijau.
Pada kenyataannya, sistem ini ternyata memakan waktu lama pada waktu triase. Akibatnya, aliran pasien eksternal sangat terhambat, dan pasien menumpuk banyak di zona pelayanan triase. Kami masih berupaya mencari solusi agar identifikasi dapat dilakukan dengan cepat dan sedini mungkin tanpa harus membebani zona triase dengan antrian pasien yang sedemikian panjang.
Pengalaman RS Panti Rapih dalam menyusun dan mensimulasikan RPBRS dapat menjadi pelajaran berharga bagi rumah sakit lain. Tentunya bukan demi keberhasilan akreditasi rumah sakit saja. Lebih penting untuk memastikan sistem keselamatan di rumah sakit dapat berjalan dengan baik lewat perencanaan yang matang. Ingat kata Benjamin Franklin, salah satu founding fathers negeri Paman Sam yang pernah menasihati kita, "By failing to prepare, you are preparing to fail". Gagal mematangkan rencana berarti kita merencanakan kegagalan. Salam keselamatan!
Robertus Arian Datusanantyo
Kepala Instalasi Gawat Darurat RS Panti Rapih
Catatan: Tulisan ini adalah opini pribadi.